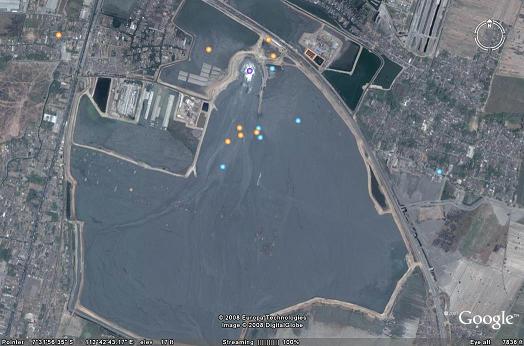
Berikut ini beberapa petunjuk awal yang mengindikasikan adanya perselingkuhan pemilik modal dan para penyelenggara negara dalam kasus semburan lumpur Lapindo yang dikumpulkan dari berbagai sumber bahan bacaan.
Pelanggaran Tata Ruang Wilayah Sidoarjo
Peraturan Daerah (Perda) mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidoarjo tahun 2003-2013 misalnya, menyatakan bahwa kawasan Porong, khususnya wilayah Siring, Renokenongo dan Tanggulangin adalah wilayah pemukiman dan budidaya pertanian. Namun, konsultan Amdal (Analisa mengenai dampak lingkungan) dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, sebuah perguruan tinggi milik negara, bersikeras bahwa Lapindo diperbolehkan beroperasi di wilayah tersebut (Lapindo, Tragedi kemanusiaan dan Ekologi, Walhi, 2008).
Anehnya, para Insinyur yang selama studinya disubsidi oleh uang rakyat itu tiba-tiba menjadi buta terhadap persoalan tata ruang wilayah. Celakanya, para pejabat publik pun dibuat kehilangan akal sehatnya di hadapan para Insinyur alumni Perguruan Tinggi Negeri (PTN) ternama yang telah dibayar Lapindo menjadi konsultannya.
Adanya Invisible Hand dari Kepres 12/2006 ke Perpres 14/2007
Pada tahap awal, pemerintah mengeluarkan Kepres No. 13 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo (yang kemudian disingkat Timnas). Kepres No 13/2006 diktum kelima menyebutkan “Dengan terbentuknya Tim Nasional dengan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga tidak mengurangi tanggung jawab PT. Lapindo Brantas untuk melakukan penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup dan masalah sosial yang ditimbulkannya”
Regulasi itu kemudian diganti oleh Perpres 14/2007 yang justru terasa adanya invisible hand (tangan-tangan tak tampak) yang berupaya meringankan bahkan menghilangkan tanggung jawab PT. Lapindo atas semburan lumpur itu (Sumber: Lapindogate, Skandal Industri Migas, 2007)
Pertama, dalam Perpres 14/2007 terdapat pembagian wilayah kelola yang menjadi tanggung jawab negara dan Lapindo (pembuatan peta terdampak dan di luar peta terdampak). Padahal sebelumnya semua menjadi tanggung jawab Lapindo akibat kelalaiannya melakukan pengeboran.
Kedua, skema penanganan dampak sosial dan lingkungan direduksi menjadi skema jual beli. Pertanyaanya tentu saja adalah apakah dampak sosial dan ekologi bisa diselesaikan dengan skema jual beli asset?
Dari kedua peraturan tersebut, tercium aroma tak sedap dari sebuah perselingkuhan antara korporasi dan penyelenggara negara.
Tawaran Cash and Resettlement
Belum jelas upaya pembayaran dengan skema 20% dan 80%, Lapindo kembali menawarkan skema resettlement (penempatan kembali) korban Lapindo ke perumahan yang dibangun oleh group Bakrie.
Tentu saja skema yang ditawarkan oleh Lapindo ini menguntungkan korporasi tersebut. Ibarat mengeluarkan uang dari kantong kiri untuk kemudian dimasukan ke kantong kanan. Anehnya, akal-akalan semacam ini juga dibiarkan saja oleh para ‘pangeran’ di negeri ini.
Pemberian Proyek Jalan Tol Kanci-Pejagan di Kabupaten Cirebon Kepada PT. Bakrie Brother
Tidak dapat dipungkiri, semburan lumpur panas di Sidoarjo ini telah memaksa Lapindo mengeluarkan uangnya guna memenuhi kewajiban dari pemerintah untuk membeli asset korban Lapindo.
Pertanyaan berikutnya tentu saja adalah apakah Lapindo rugi atau telah mengalami kebangkrutan?
Ternyata tidak, menurut Syaefudin Simon, dalam tulisanya yang berjudul ‘Lapindo Undercover’ menyebutkan bahwa bersamaan dengan pelaksanaan proses ‘ganti rugi’ terhadap korban Lapindo itu, pemerintah memberikan proyek jalan tol (Kanci-Pejagan di Kabupaten Cirebon) kepada PT. Bakrie Brother senilai Rp. 1.3 trilyun. Nilai proyek tersebut hampir sama dengan biaya ganti rugi warga Perumtas.
Anehnya, jaminan kredit Bakrie kepada sindikasi perbankan untuk membangun jalan tol itu adalah garansi pemerintah.
lengkap sekali kak infonya
BalasHapusmacam macam tepung dan kegunaannya